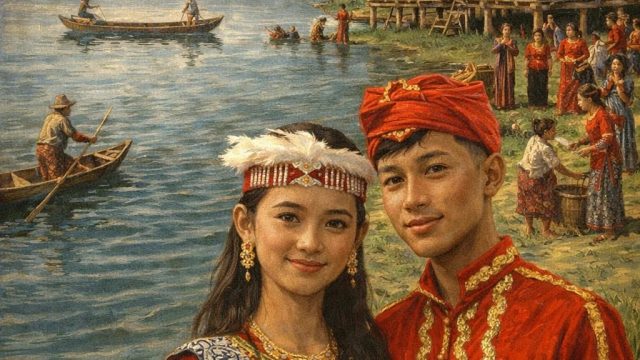Di sudut waktu yang nyaris terlupakan, di sebuah kampung kecil yang kini telah menjadi kelurahan di jantung Kota Parigi, Sulawesi Tengah, hidup sebuah kisah mistik yang terus hidup dalam bisik-bisik malam dan kenangan masa kanak-kanak. Namanya Kalomba. Ia bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sosok yang diyakini muncul dari kabut senja—Siluman Kambing yang melangkah mundur, mengendus aroma ampas kelapa, dan menakuti tawa riang anak-anak yang tak tahu batas.
Kalomba adalah teror masa kecil. Bila suara kami meninggi saat petang menjelang, cukup disebut namanya, maka ketakutan segera membungkam. Apa Kalomba sebenarnya? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi di antara para tetua kampung, termasuk kakek saya, almarhum Ismail Saribu, mengatakan itu adalah makhluk bertubuh kambing dengan bulu lebat, dan—yang paling aneh—berjalan mundur. Ia muncul malam hari, mencari ampas kelapa yang dibuang sembarangan, konon sebagai santapannya.
Ada pula versi lain: Kalomba bukan sekadar siluman pengganggu, tetapi bisa dipelihara oleh manusia yang menginginkan wibawa dan kesaktian. Namun siapa yang pernah melihatnya? Tak ada. Bahkan saya yang tumbuh di sisi rumpun bambu kuning yang diyakini sebagai sarangnya, tak pernah sekalipun bertemu makhluk itu. Tapi ketidakhadiran bukanlah ketiadaan. Mitos tidak hidup dari bukti, tapi dari keyakinan dan rasa takut.
Warisan Kearifan
Nenek saya, Ma’ani, adalah penjaga kisah-kisah klasik macam itu. Ia mencintai sayur santan dan nasi uduk, sebab itu kelapa adalah bagian dari hidupnya. Tapi ia sangat berhati-hati. Setiap sore, ampas kelapa tidak pernah dibuang sembarangan. Ia menyimpannya untuk keesokan hari—sebuah ritual kecil yang konon menghindarkannya dari Kalomba.
Saya mulai mengingat kembali kisah ini ketika membaca Rumah di Atas Kahayan karya LR. Baskoro, yang menyinggung Kambe—siluman berkepala kambing berbadan manusia. Mirip, tetapi berbeda. Kalomba bukan hanya siluman, tapi juga simbol ketakutan yang dibentuk oleh waktu, tempat, dan budaya. Ia adalah mitos hidup dari Parigi.
Topeule, Sang Pemangsa Senyap
Namun, di antara segala ketakutan mistik Parigi, Kalomba hanya menempati urutan kedua. Di atasnya berdiri Topeule—atau Pongko. Ia adalah manifestasi dari kegagalan manusia memahami dan menguasai ilmu gaib. Tubuhnya ditinggal, hanya kepala yang terbang melayang mencari mangsa: anak-anak dan perempuan. Darahnya menetes, suaranya dikenal dari dentuman aneh yang disebut “Pokpok”.
Di Parigi, ada bahasa yang melukiskan itu: “Jika suaranya keras, ia masih jauh. Tapi bila sayup, maka ia sudah mengintai di dekatmu.”
Saya sendiri, entah kebetulan atau nasib, pernah mendengar suara itu. Sekali saat kecil di Masigi, sekali lagi ketika menjadi mahasiswa dan menyusuri gua-gua Bambaloka di Sulawesi Barat. Suara Pokpok itu begitu nyata di telinga, tapi tak ada yang muncul dari balik gelap. Saya pun tetap ragu, meski bulu kuduk sempat berdiri.
Konon orang-orang yang menjadi Topeule karena gagal menguasai ilmu gaib atau ilmu hitam yang mereka pelajari—konon masih hidup seperti manusia biasa. Tak ada yang aneh di siang hari. Tapi waspadalah bila mereka datang pagi-pagi meminta garam. Sebab itu tanda klasik dari orang yang mempelajari ilmu hitam itu. Dan untuk menjaga diri, berilah apa yang mereka minta.
Mitos yang Menyatu dengan Waktu
Kalomba dan Topeule adalah dua wajah dari masa lalu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Mereka hadir sebagai dongeng, sekaligus alat didik. Orang tua zaman dahulu tak mengenal psikolog anak, tak tahu apa itu parenting modern. Tapi mereka tahu satu hal: anak-anak takut pada sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Maka mereka menciptakan Kalomba. Maka mereka mewariskan kisah Topeule.
Kini, di zaman ketika anak-anak lebih takut kehilangan sinyal daripada hantu, kisah-kisah seperti ini mungkin terdengar usang. Tapi di malam-malam tertentu, saat lampu padam dan suara binatang malam mulai merambat, bisik-bisik soal Kalomba kembali terdengar di ujung kampung. Seolah berkata: “Aku belum mati. Aku hanya menunggu kalian lupa.”
Kalomba mungkin hanya mitos. Sesuatu yang tidak pernah ada. Tapi seperti semua mitos, ia hidup bukan dari kebenaran, melainkan dari kebutuhan manusia untuk merasa kecil di hadapan yang gaib.
Dan mungkin, itu sebabnya kita masih butuh mitos Kalomba dan Topeule. ***