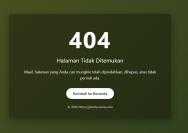Musim dingin 1942. Dunia memanas. Di tanah air, Jepang menguasai Hindia Belanda. Di Eropa, Hitler mengepung segalanya. Dan Belanda, negara kecil yang dulu mengirim kapal dan komisaris ke tanah-tanah tropis, tak lagi berkuasa atas dirinya sendiri.
Di sebuah rumah kayu berwarna hijau zaitun di pinggiran Leiden, Sara menyeduh teh sambil menggulung surat kabar yang menakutkan: kolom depan menuliskan “Nederland bezet, Pemerintahan dalam pelarian”.
“Willem,” bisiknya lirih, “apa artinya ini bagi kita?”
Suaminya kini tidak lagi mengenakan seragam, melainkan pakaian lusuh dan wajah yang lebih tua dari usia. “Artinya, kita tidak punya negara. Tapi kita masih punya rumah. Masih punya satu sama lain.”
Namun kekacauan tak bisa terus ditahan.
Rumah mereka disatroni tentara. Orang timur seperti Sara dicurigai. “Mungkin ia mata-mata Inggris. Atau Yahudi dari Asia?” bisik tetangga. Suatu malam, mereka membawa Willem, untuk ditanyai. Tapi tak pernah kembali.
Sara tinggal sendiri bersama anak-anak yang sudah tumbuh remaja. Ia menjahit, mencuci untuk tetangga, menunggu kabar yang tak pernah datang. Beberapa percaya Willem mati di kamp tawanan Jerman. Yang lain bilang ia melarikan diri ke Inggris.
Tapi Sara, yang tak lagi dipanggil Sari, tetap menanti.
Satu-satunya warisan dari Willem adalah sepetak tanah kecil di luar Leiden, yang kemudian ia kelola sebagai ladang bunga. Ia hidup dari bunga-bunga yang mekar setiap musim semi. Tetap menyimpan kalung emas dari Willem, tetap membaca surat Lastri setiap ulang tahun kematiannya.
Ia hidup lama. Tua. Tapi tidak pernah menikah lagi.
Tahun 1971. Sebuah tim sejarah dari Universitas Amsterdam meneliti jejak zeebaboe dalam migrasi kolonial. Mereka menemukan peti tua di loteng rumah tua Sara, yang sudah wafat lima tahun sebelumnya.
Di dalamnya: Surat Lastri, lalung emas, foto hitam-putih Annelies kecil dipeluk perempuan berkulit sawo matang, dan sepucuk surat tak terkirim, ditujukan pada “Kementerian Kolonial yang Sudah Tidak Ada”:
“Kami datang bukan hanya untuk merawat anak-anak kalian. Kami datang dengan hati. Ada yang kembali ke laut, ada yang menetap di tanah dingin ini. Tapi kami semua… ingin dikenang.”
Sara van der Woude, zeebaboe.
Dan hari ini, kalau kau menyeberangi lautan dari Batavia yang kini Jakarta ke Rotterdam, dan malam sedang basah oleh hujan, konon… kau masih bisa mendengar suara perempuan bernyanyi di lorong kapal. Suara yang halus, lembut, kadang sendu—lagu pengantar tidur dalam bahasa yang sudah hampir dilupakan.
Dan bila kau bermata tipis, seperti cenayang, mungkin kau akan melihat siluet perempuan berkebaya, menatap ke cakrawala. Menunggu. Bukan untuk kekasih yang hilang, tapi agar kisahnya tak kembali dikubur ombak sejarah.