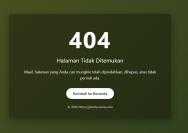Roman pendek berjudul “Zeebabu, Duka di Tanah Bersalju” ini terinspirasi dari kisah nyata tentang para “Zeebaboe”, perempuan-perempuan Indonesia yang dibawa berlayar ke Belanda untuk menjadi pengasuh anak, dan hidup dalam bayang sejarah yang dilupakan.
Kapal SS Prinses Amalia mengerang lembut saat meninggalkan pelabuhan Batavia. Di dek kelas dua, seorang gadis muda berdiri memandangi laut luas, rambut hitamnya berkibar tertiup angin asin. Namanya Sari. Tapi bagi anak-anak Belanda yang diasuhnya, ia adalah “Zeebaboe“. Si pengasuh dari negeri yang sebentar lagi akan ia tinggalkan.
“Zeebaboe, aku ingin susu,” rengek Annelies, gadis kecil berambut pirang.
Sari tersenyum, membungkuk lembut, dan berkata dalam bahasa Belanda patah-patah, “Sebentar, ik haal het voor je.”
“Hmm… pengucapanmu lebih baik dari minggu lalu,” kata suara berat di belakangnya.
Sari menoleh. Di sana berdiri pria jangkung berseragam kolonial abu-abu. Matanya biru kelam seperti laut yang sedang ia layari. Tuan van der Woude. Duda muda itu tersenyum, angin mengibaskan ujung rambut cokelatnya yang mulai memutih.
“Saya belajar dari Hendrik kecil, Tuan,” jawab Sari, matanya tertunduk. Tapi ia tak bisa menahan senyum tipis.
“Jangan panggil saya ‘Tuan’ saat kita hanya berdua,” katanya lembut. “Panggil saja Willem.”
Sari tertawa pelan. “Kalau begitu Willem juga jangan panggil saya ‘Zeebaboe’. Nama saya Sari.”
Ia berani sekarang. Pelayaran baru dimulai dua hari, tapi jarak mereka sudah tak sejauh Batavia ke Rotterdam.
“Baiklah… Sari,” kata Willem, mengecap namanya perlahan seolah mengeja mantera. “Tahukah kamu, Sari artinya sutra dalam bahasa Latin?”
“Tidak. Tapi dalam bahasa saya, itu nama bunga,” sahut Sari, matanya mengerling.
“Jadi kamu bunga yang mekar di tengah laut,” gumam Willem. “Dan aku seorang pelaut kesepian yang tersihir olehnya.”
Sari menunduk, jantungnya berdebar. “Tuan…maaf…Willem… hati-hati. Kapal ini penuh mata dan telinga.”
“Biarlah. Lautan adalah dunia lain, bukan?” Willem mencondongkan badan, membisik, “Di sini, kita bisa menjadi siapa saja.”
Dan sore itu, di tengah lautan, saat matahari jatuh perlahan ke kaki langit, bibir mereka nyaris bersentuhan, tapi tidak. Masih ada batas, masih ada bisikan rasa bersalah. Tapi mereka tahu, itu hanya soal waktu.