Subuh datang tanpa cahaya. Langit Makassar menggantung abu-abu, seolah enggan memilih antara siang dan malam. Di dermaga kecil di belakang rumah Majestra, laut berdesir pelan, memantulkan cahaya lampu minyak yang masih menyala sejak malam pemakaman.
Surajati berdiri di tepi papan kayu yang lembap. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, tanpa alas kaki. Di hadapannya, tubuh La Ode Rerassa dibaringkan di atas perahu kecil—bukan untuk dikubur, melainkan untuk ritual terakhir sebelum jenazah dibawa ke tanah keluarga.
Ini bukan bagian dari hukum negara. Ini bagian dari hukum yang lebih tua.
Di sekeliling dermaga, para lelaki tua Bugis berdiri melingkar. Tidak banyak. Tidak perlu. Yang hadir adalah mereka yang tahu—dan mereka yang akan mengingat.
Nenek Bonea muncul dari bayangan, tubuhnya kecil namun tegak. Rambutnya putih seluruhnya, disanggul ketat. Tongkat kayu di tangannya bukan alat bantu berjalan, melainkan penanda otoritas. Bahkan Daeng Ranrang, yang berdiri beberapa langkah di belakang Surajati, menundukkan kepala saat perempuan tua itu mendekat.
“Air menyimpan lebih banyak rahasia daripada tanah,” kata Nenek Bonea pelan. “Maka sumpah di atas laut tidak boleh ringan.”
Ia menoleh pada Surajati. “Kau anak yang lama pergi.”
Surajati tidak membantah.
“Apakah kau masih ingat caranya bersumpah?”
Surajati menatap laut. “Aku ingat.”
Nenek Bonea mengangguk. Ia memberi isyarat. Seorang lelaki maju membawa sebilah badik pendek, gagangnya dari tanduk kerbau, bilahnya kusam oleh usia.
Surajati menerima badik itu tanpa ragu. Ia tahu apa yang diminta.
Ia menggores telapak tangannya sendiri—tidak dalam, tapi cukup. Darah menetes ke air laut di bawahnya, larut seketika.
“Apa sumpahmu?” tanya Nenek Bonea.
Surajati menarik napas. Kata-kata terasa berat di lidahnya, tapi ia mengucapkannya juga.
“Aku bersumpah menjaga kehormatan darahku. Tidak lari dari akibat. Tidak mengkhianati nama.”
Laut bergelombang kecil, seolah menjawab.
Nenek Bonea menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. “Laut sudah mendengar.”
Dari sudut matanya, Surajati melihat Ranuma memperhatikan ritual itu dengan senyum tipis. Bukan senyum bangga—melainkan senyum orang yang mencium peluang.
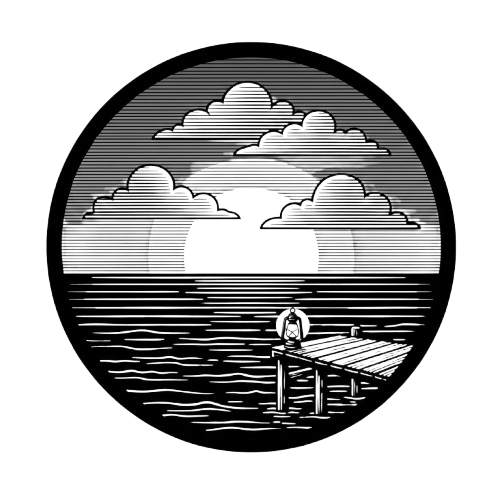
Serangan itu terjadi satu jam kemudian.
Daeng Ranrang baru saja kembali ke rumah setelah ritual. Ia duduk di beranda depan, meminum kopi pahit tanpa gula. Surajati berdiri di dekat tiang, sementara Safira mengamati dari jarak beberapa meter, wajahnya tegang.
Suara mesin motor terdengar mendekat—lebih dari satu. Terlalu cepat. Terlalu terbuka.
Safira bergerak lebih dulu. “Puang,” katanya pendek.
Terlambat.
Tembakan pertama memecah udara. Kayu berderak. Lampu minyak pecah, menyiramkan api kecil ke lantai. Orang-orang berteriak. Ranuma menghilang ke balik pilar.
Surajati bergerak refleks, mendorong ayahnya ke lantai, menutupi tubuhnya dengan tubuh sendiri. Tembakan kedua menghantam tiang di belakang mereka.
Suara balasan datang dari dalam rumah. Senjata tua, tapi di tangan orang yang tahu cara menggunakannya. Kekacauan berlangsung tidak lebih dari dua menit—namun terasa seperti seumur hidup.
Ketika semuanya berakhir, dua penyerang tergeletak di tanah. Satu melarikan diri ke arah laut.
Daeng Ranrang terengah, matanya terbuka lebar. Tidak ada darah di tubuhnya, tapi tangannya gemetar—bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang ditahan terlalu lama.
“Masuk,” katanya kepada Surajati. Suaranya serak.
Di dalam kamar besar, Daeng Ranrang duduk di ranjang. Safira memeriksa sekeliling. Ranuma masuk terakhir, wajahnya penuh amarah yang dibuat-buat.
“Ini peringatan,” kata Ranuma. “Mereka menguji kita.”
Daeng Ranrang menatapnya dingin. “Tidak ada yang menguji rumah ini tanpa niat membakar.”
Ia menoleh pada Surajati. “Kau lihat sendiri.”
Surajati mengangguk. Dadanya masih sesak oleh adrenalin. Ia tidak berkata bahwa ia hampir mati dengan perasaan yang aneh: tenang.
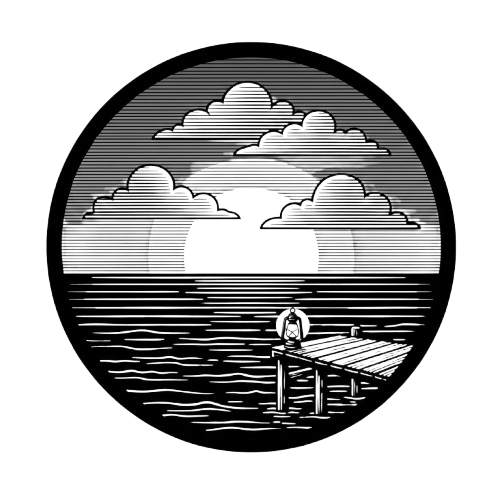
Malam itu, setelah rumah kembali sunyi, Daeng Ranrang memanggil Surajati ke ruang kerja.
Ruangan itu penuh buku lama, peta laut, dan dokumen yang tidak pernah dilihat orang luar. Bau kayu dan kertas tua bercampur dengan asap rokok kretek.
“Aku tidak akan lama,” kata Daeng Ranrang tiba-tiba.
Surajati terdiam. “Ayah baik-baik saja.”
Daeng Ranrang tersenyum tipis. “Tubuh bisa dibohongi. Waktu tidak.”
Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map cokelat tua. Mendorongnya ke arah Surajati.
“Ini daftar orang yang kau tidak boleh percaya.”
Surajati membuka map itu perlahan. Nama-nama muncul. Beberapa ia kenal. Beberapa mengejutkannya.
Termasuk satu nama dari Sumatera: Malikara.
Dan satu dari Jawa: Raja Adi Wiraguna.
“Arjuna?” tanya Surajati pelan.
Daeng Ranrang tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, ke arah laut gelap.
“Anak sulung selalu ingin memerintah tanpa darah,” katanya akhirnya. “Tapi darah selalu punya rencana sendiri.”
Di luar ruangan, Safira berdiri menjaga. Di kejauhan, laut kembali bergelombang—tenang, seolah tidak pernah menyaksikan sumpah, darah, dan peluru dalam satu pagi.
Surajati menutup map itu perlahan.
Ia mengerti sekarang: kepulangannya bukan kebetulan.
Itu adalah pemanggilan.
Dan laut telah mencatat namanya kembali.
Bersambung ke Darah di Tanah Warisan #3: Anak Sulung dan Jalan Halus




