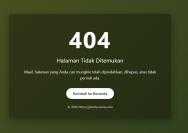Hujan turun deras sejak sore, membungkus kota Makassar dengan suara yang menenggelamkan doa. Langit hitam, laut gelisah, dan angin membawa bau besi yang tidak menyenangkan, bau yang oleh orang-orang tua disebut sebagai pertanda.
Daeng Ranrang Majestra bersikeras keluar rumah malam itu.
“Aku tidak akan bersembunyi di balik tiang rumah sendiri,” katanya datar, sambil merapikan sarung dan jas tipis yang biasa ia kenakan saat menemui orang luar.
Surajati berdiri di ambang pintu. “Ayah tidak perlu datang sendiri.”
Daeng Ranrang menatapnya. “Seorang puang yang berhenti terlihat akan segera dilupakan.”
Ranuma tersenyum miring dari sudut ruangan. “Biar aku ikut.”
“Tidak,” potong Daeng Ranrang. “Kau tinggal.”
Ranuma terdiam, matanya menyempit.
Safira berdiri tak jauh, wajahnya tegang. Ia sudah mencium ada sesuatu yang salah sejak sore, pergerakan orang-orang, pesan singkat yang terputus, dan keheningan yang terlalu rapi.
Mobil hitam itu melaju menembus hujan. Di dalamnya hanya ada Daeng Ranrang, Surajati, dan sopir lama yang setia. Jalanan licin, lampu-lampu toko memantul di aspal basah seperti bayangan yang berlari.
Pertemuan itu seharusnya sederhana: seorang pengusaha pelabuhan lama yang ingin “berdamai”.
Tidak ada pertemuan sederhana di dunia ini.

Di tikungan sempit dekat gudang tua, semuanya terjadi terlalu cepat.
Lampu depan menyilaukan. Rem mendecit. Dari sisi kanan, sebuah motor muncul tanpa lampu. Dari kiri, suara letupan memecah hujan.
Surajati bergerak refleks. Ia menarik ayahnya ke bawah, tapi satu tembakan sudah lebih dulu menemukan sasaran.
Daeng Ranrang terhuyung. Tubuhnya menghantam kursi, lalu lantai mobil.
Sopir berteriak. Mobil oleng. Kaca pecah. Hujan masuk bersama bau mesiu.
Surajati merangkul ayahnya. Darah mengalir dari dada kiri, membasahi kain putih yang dikenakannya.
“Ayah!” teriak Surajati.
Mata Daeng Ranrang terbuka, tapi pandangannya kabur. Tangannya meraba udara, menemukan tangan Surajati, menggenggamnya erat.
“Dengar,” bisiknya. Suaranya tenggelam oleh hujan. “Jangan balas dengan emosi.”
Surajati menggeleng. “Ayah jangan bicara.”
Daeng Ranrang tersenyum lemah. “Aku jatuh… bukan karena peluru.”
Surajati menunduk, menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mobil berhenti. Orang-orang berlari. Dunia berubah menjadi suara sirene dan langkah kaki.

Rumah sakit malam itu penuh dengan cahaya putih dan bau antiseptik. Dokter bergerak cepat, perawat berlari, dan orang-orang Majestra berdiri kaku di lorong seperti patung yang lupa caranya bernapas. Kabar Puang Rera, begitu Daeng Ranrang disapa, tertembak dan kritis, menyebar jauh seperti badai.
Ranuma datang dengan wajah pucat dan amarah yang tak tersalurkan. “Siapa?” tanyanya kasar.
“Belum tahu,” jawab Safira pendek. “Dan jangan buat kita terlihat panik.”
Ranuma mencengkeram dinding. “Mereka menembak ayah!”
“Dan itulah sebabnya kau harus tenang,” balas Safira. Matanya dingin.
Pintu ruang operasi tertutup. Waktu melambat, lalu berhenti sama sekali.
Surajati duduk sendiri di bangku besi. Bajunya masih basah oleh hujan dan darah. Ia menatap tangannya, tangan yang tadi menggenggam darah ayahnya. Tidak gemetar. Tidak kosong.
Ia sadar akan satu hal yang mengerikan: ketakutannya sudah mati.

Dokter keluar dua jam kemudian.
“Nyawanya selamat,” katanya. “Tapi peluru mengenai saraf. Beliau mungkin tidak akan berjalan seperti dulu. Dan… kemampuannya berbicara bisa terganggu.”
Kalimat itu jatuh seperti vonis.
Ranuma mengumpat pelan. Safira menutup mata sejenak. Surajati mengangguk, bukan sebagai anak, melainkan sebagai seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti.
Ayahnya hidup.
Namun Puang Rera itu telah jatuh.

Keesokan harinya, rumah Majestra berubah. Orang-orang datang bukan lagi untuk memberi hormat, tapi untuk melihat celah. Telepon berdering tanpa henti. Nama Malikara disebut lebih sering, diikuti bisik-bisik tentang Arjuna yang belum pulang.
Surajati duduk di ruang kerja ayahnya. Safira berdiri di dekat pintu. Ranuma mondar-mandir seperti harimau terkurung.
“Aku akan membunuh Malikara,” kata Ranuma.
“Dan setelah itu?” tanya Surajati tenang. “Kita perang terbuka dengan Sumatera? Memberi Arjuna alasan untuk mengambil alih?”
Ranuma berhenti. “Kau mulai terdengar seperti dia.”
Surajati menatap meja ayahnya, tongkat kayu yang kini bersandar tak terpakai. “Aku mulai terdengar seperti orang yang ingin kita tetap hidup.”
Sunyi menekan ruangan.
Safira melangkah maju. “Kita butuh pemimpin sementara.”
Ranuma menoleh cepat. “Itu aku.”
Safira menatapnya datar. “Pemimpin bukan yang paling keras.”
Semua mata beralih ke Surajati.
Surajati mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya tidak ada ambisi. Hanya kejelasan.
“Aku tidak ingin ini,” katanya. “Tapi aku tidak akan membiarkan keluarga ini dihabisi satu demi satu.”
Di kamar rumah sakit, Daeng Ranrang terbaring dengan mata setengah terbuka. Surajati duduk di sampingnya.
Ayahnya menggenggam tangannya lemah, jari-jarinya gemetar. Dari bibir yang sulit bergerak, keluar satu kata yang hampir tak terdengar:
“Jaga.”
Surajati mengangguk.
Di luar jendela, hujan berhenti. Tapi tanah sudah basah, dan jejak darah tidak bisa dihapus begitu saja.
Karena ketika ayah jatuh,
anak tidak lagi punya pilihan selain berdiri di tempatnya.
Bersambung ke Darah di Tanah Warisan #6: Tiga Anak, Tiga Jalan