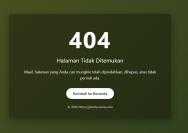Angin malam di tengah Laut Arab berembus dingin. Di geladak kapal, lampu-lampu minyak berayun pelan, menebarkan cahaya kekuningan yang lembut. Anak-anak telah tidur, dan hanya suara mesin kapal serta debur ombak yang mengisi sunyi.
Sari duduk di bangku kayu dekat pagar dek, mengenakan selendang tipis yang ia bawa dari kampung. Ia mengusap pipinya pelan, menahan dingin dan sesuatu yang lain… sesuatu yang tak ia mengerti.
Lalu langkah kaki mendekat. Ia tak perlu menoleh. Ia tahu siapa.
“Tak bisa tidur?” suara itu datang seperti pelukan hangat.
“Aku terbiasa dengan suara jangkrik dan angin sawah. Di sini, terlalu banyak besi yang berisik,” jawab Sari pelan.
Willem tertawa kecil dan duduk di sampingnya. “Aku juga. Tapi aku mulai terbiasa dengan suara lain. Suaramu, misalnya.”
Sari tertawa, geli, tapi dalam tawanya ada semburat malu. “Tuan… suka menggoda.”
“Aku tidak menggoda. Aku memuji.” Ia menoleh padanya. “Sari… pernahkah kau berpikir, bahwa mungkin takdir sedang bermain-main dengan kita?”
Sari memandangi langit. “Takdir? Bagiku takdir itu keras. Ia menaruhku di rumah-rumah orang asing, membuatku mengasuh anak-anak yang bukan darahku.”
“Tapi takdir juga menaruhmu di kapalku.”
Hening sejenak. Sari bisa merasakan mata pria itu menatapnya, bukan seperti seorang tuan memandang babu, tapi seperti seorang lelaki memandang perempuan yang ia inginkan.
“Kau perempuan paling lembut yang pernah kutemui. Seandainya dunia tak punya warna kulit…”
Sari menoleh cepat. “Jangan berkata begitu.”
“Kenapa tidak?” bisik Willem. Ia menggenggam tangan Sari. “Apa salahnya mencintai seseorang yang membuat hari-hariku terasa hidup lagi? Yang membuat Annelies tertawa dan Hendrik bisa tidur pulas. Yang membuatku merasa… aku masih punya hati.”
Tangan Sari gemetar dalam genggamannya. “Tapi di darat nanti, semua ini akan lenyap. Kau akan jadi komisaris lagi. Aku akan kembali jadi pelayan.”
“Kalau aku minta kau tetap tinggal bersamaku? Di rumahku, di Leiden?”
“Maksudmu… jadi istrimu?”
“Aku tak tahu apakah dunia akan mengizinkan. Tapi kalau tidak, biarlah aku tetap jadi pelaut, dan kau jadi lautku.”
Dan malam itu, sebelum kapal mencapai Laut Merah, bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama, sunyi, pelan, tapi penuh badai yang belum datang.